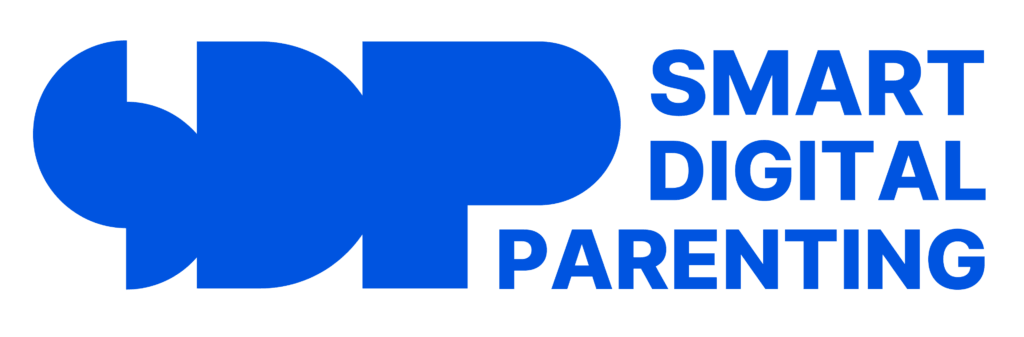digitalMamaID — Pada setiap perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu mengandung elemen kekerasan berbasis gender. Perempuan dan anak-anak harus menanggung dampak paling berat atas hilangnya ruang hidup rakyat oleh negara maupun korporasi.
“Pada kampung atau hutan yang dibakar ada ibu hamil yang sesak napas dan ibu yang menangis karena hal pertama yang ia pikirkan adalah seragam dan buku-buku sekolah anaknya yang harus dibawa sekolah esok hari,” kata aktivis perempuan Kalis Mardiasih dalam orasinya berjudul Bangkitnya Gerakan Perempuan dalam Pusaran Penindasan Berlapis pada Festival Bandung Menggugat di Dago Elos, Bandung, Sabtu, 12 April 2025.
Ia mengatakan, penggusuran yang berdampak kemiskinan itu selalu diikuti dengan terputusnya akses pendidikan dan ekonomi perempuan. Tidak itu saja, ada pula perkawinan usia anak, siklus kekerasan dalam rumah tangga, stunting, gizi buruk, dan banyak lagi.
Kelompok ibu menjadi pemimpin pergerakan di berbagai pelosok negeri, tapi sekaligus menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran politik praktis kaum oligarki dengan harga paling murah. Ia mencontohkan situasi belakangan yang menyeret politisi elit yang terlilit korupsi. Perkara ini diwarnai dengan keributan soal perselingkuhan. “Sebab selama ini elit itu dikenal sebagai politisi yang banyak disukai ibu-ibu karena romantis dan relijius. Romantis dalam imajinasi patriarki,” katanya. Keributan ini berhasil menyedot perhatian masyarakat. Revisi UU TNI, UU Polri jadi tidak lagi terdengar.
Hari-hari belakangan nyaris dipenuhi kabar buruk yang menimpa perempuan. Kekerasan seksual oleh Kapolres Ngada, perempuan adat di Papua yang terusir dari tanahnya sendiri, perempuan di Morowali yang bergelut dengan pencemaran lingkungan akibat proyek strategis nasional. Belum lagi soal pelaksanaan program Makan Bergizi (Tidak) Gratis yang compang-camping, memberi makanan ultra-proses dan tinggi gula. Aktivis yang akun media sosialnya diretas dan jadi korban doxxing. Ada pula yang dipanggil polisi karena kontennya dianggap memprovokasi.

Menjaga nyala perlawanan
Di tengah situasi itu, perlawanan tak boleh berhenti. Kalis menyampaikan empat cara untuk menjaga nyala perlawanan. Satu, memilih teman dalam keberpihakan. “Saya menyadari, berkompromi dengan teman yang meninggalkan kelompok lemah dan tertindas itu tidak sehat. Tidak bisa berkompromi dengan orang-orang yang jujur, siap menikam dari belakang sewaktu-waktu. Masih banyak teman yang mengimani kesetaraan, antimisoginisme, untuk hidup jujur. Napas pergerakan kita akan panjang untuk tidak berkompromi dalam memilih kawan,” tuturnya.
Dua, sekecil-kecilnya perlawanan adalah perlawanan. Alat negara yang sering hadir menyerang gerakan mahasiswa dan rakyat itu disiapkan dalam waktu lama. Barisan meraka kokoh, sementara fokus masyarakay semakin terbelah. “Mulai kembali mencintai yang kecil. Kelompok membaca yang kecil. Kelompok seni yang kecil tapi dikenali dan menyapa rakyat. Organisasi kecil yang membawa kejujuran kepada rakyat. Kecil itu mudah, kokoh dan tidak goyah. Kecil tapi berlipat banyak dan menular,” katanya.
Tiga, menolak sikap pengkultusan si paling gerakan, khususnya gerakan perempuan. Menolak bentuk penyeragaman gerakan perempuan yang bersumber dari narasi patriarki. “Belakangan orang menyebut perempuan berdaya yang modern adalah yang beragumen rasional dan tidak emosional maupun sentimentil. Ini menihilkan gerakan perempuan,” kata Kalis. Perempuan Kendeng yang menyemen kakinya, ibu-ibu petani Rembang yang mewalawan dengan bersalawat di sawah. Gerakan mereka emosional dan jauh dari imajinasi perempuan moder yang rasional.
Empat, pentingnya panduan keamanan holistik. “Gerakan rakyat bisa menang saat kita tidak lengah, tidak mati, tidak diculik dan tidak hilang. Jadi menjadi aktivis pergerakan rakyat bukan berarti harus hidup di ruang yang tidak aman dan tidak sehat,” katanya. Saling menguatkan untuk menjaga kawan, memberi panduan keamanan fisik, psikis, digital harus jadi prioritas.
Festival Bandung Menggugat
Di tengah derasnya gelombang ketimpangan sosial, perampasan ruang hidup, dan menyempitnya demokrasi, Festival Bandung Menggugat hadir sebagai ruang perlawanan kolektif yang berangkat dari kegelisahan dan keberanian. Diselenggarakan di Dago Elos—wilayah yang tengah berjuang melawan ancaman penggusuran—festival ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan kritis yang digagas BandungBergerak bersama komunitas dan mahasiswa sejak enam bulan terakhir.
Festival ini lahir dari kerja-kerja panjang: mulai dari diskusi kampus, pelatihan penulisan esai opini, penyelenggaraan sayembara, hingga peluncuran buku Mahasiswa Bersuara yang memuat 28 tulisan dari mahasiswa berbagai daerah. Buku ini telah dibawa keliling ke kampus dan warung kopi sepanjang Maret untuk dibedah dan didiskusikan. Kini, semangat itu bermuara di Dago Elos—menjadi peristiwa bersama yang melibatkan banyak pihak.

Tri Joko Her Riadi, Pemimpin Redaksi BandungBergerak, dalam pengantarnya menyatakan bahwa menggugat dan melawan hari ini bukanlah pilihan eksklusif, tapi napas keseharian. “Di tengah hidup berdemokrasi yang dibajak demi kepentingan para oligarki, di tengah hidup bermasyarakat yang dikekang pemenuhan hak-hak dasarnya, di tengah hidup akademik yang ditelikung oleh nafsu penguasa, menggugat dan melawan harus menjadi keseharian. Ia menjelma napas yang membuat kita mampu bertahan. Sehari, dan sehari lagi,” tulisnya.
Festival ini mengusung berbagai agenda: diskusi publik, orasi, pertunjukan seni, pasar rakyat, hingga pameran foto perjuangan warga. Diskusi digelar sepanjang hari, membahas tema seputar krisis demokrasi, perjuangan warga Dago Elos, dan ruang kampus sebagai arena perlawanan intelektual. Sejumlah pemantik dari kalangan akademisi, jurnalis, pengacara publik, dan aktivis turut serta berbagi gagasan. Penampilan band punk Sukatani menjadi salah satu yang dinanti.

Festival ini tidak hanya menyatukan ekspresi, tetapi juga menghidupkan solidaritas. Panggung-panggung seni menampilkan teater, musik, dan orasi budaya sebagai medium menyampaikan keresahan. Pojok Bersuara dibuka bagi siapa saja yang ingin menulis keresahannya dan membagikan suara yang selama ini terpinggirkan.
Festival Bandung Menggugat menegaskan bahwa perlawanan tidak harus monumental. Ia bisa tumbuh dari hal-hal kecil, dari kerja-kerja kolektif yang konsisten, dari keberanian menyuarakan yang tak terdengar. Dan yang paling penting, dari kesadaran bahwa hidup layak adalah hak, bukan hadiah. [*]