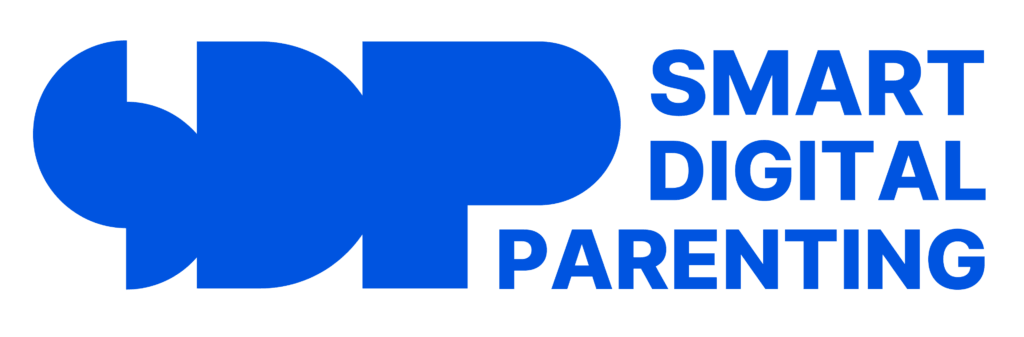digitalMamaID — Di tengah konflik agraria yang mengancam ruang hidup mereka, ibu-ibu Dago Elos menjelma menjadi wajah perlawanan warga terhadap ketidakadilan.
Kampung Dago Elos di Kota Bandung menjadi salah satu potret konflik agraria perkotaan yang masih berlangsung hingga kini. Di tengah tarik-menarik klaim lahan dan ancaman penggusuran, warga bertahan menjaga ruang hidup yang telah mereka bangun puluhan tahun. Konflik ini bukan semata soal sertifikat tanah, melainkan tentang hak tinggal, rasa aman, dan keberlanjutan komunitas di tengah kota.
Ibu-ibu Dago Elos hadir di garis depan, menjaga ruang komunitas, mengatur jalannya aksi, hingga menyuarakan tuntutan dengan suara mereka sendiri. Saat Dago Elos memanas, ibu-ibu Dago Elos merapatkan barisan, menjadi pagar yang mengamankan kampung. Aksi ini menggerakkan keberanian warga lain mempertahankan ruang hidupnya. Peran ini tumbuh dari pengalaman hidup sebagai kelompok yang paling terdampak, sekaligus paling terbiasa bertahan.
Tuti (48), warga Dago Elos mengatakan peran ini tumbuh secara alami. Konflik agraria ini tidak saja berdampak pada laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak, termasuk ibu-ibu, juga merasakannya. “Jadi, kalau misalkan nggak sama kita, sama siapa lagi? Dan ternyata memang ibu-ibu kalau di depan itu lebih sering didengar dan misalkan kita mau ngamuk gimana pun lebih aman gitu,” ungkap Tuti yang ditemui di sela-sela persiapan acara 1312 Notfest Dago Melawan, Jaga Lahan Lawan Tiran, Jumat 12 Desember 2025.

Meskipun setiap kali aksi demonstrasi rasa takut kerap kali dirasakan, namun ia menikmati semua prosesnya. Keterlibatan berulang ini lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari ibu-ibu muda, pra-lansia hingga lansia pun ingin ikut terlibat. “Semua dirangkul,” kata Tuti.
Keterlibatan itu lama-lama membawa perubahan besar bagi warga, terutama ibu-ibu. Dari awalnya tidak memahami isu agraria, perlahan mereka belajar lewat obrolan-obrolan kecil yang berkembang menjadi ruang belajar bersama.
Menurutnya, setiap aksi selalu didahului dengan upaya saling berbagi pemahaman, agar ketika turun ke jalan, warga tahu apa yang sedang diperjuangkan. “Nah, kita selalu kasih tahu jangan sampai ada yang nanya, kita nggak tahu mau ngapain gitu kan. Alhamdulillah warga teh, yang nggak tahu juga nanya ke yang tahu gitu,” terang Tuti.
Kekuatan membuat satu gerakan
Jika biasanya perempuan hanya ditempatkan di dapur, hal ini tak berlaku bagi ibu-ibu Dago Elos. Menurut seorang ibu Dago Elos lainnya, Ayang (47), hal ini terjadi lantaran warga ‘menormalisasikan hal-hal yang mungkin tidak normal untuk ibu-ibu lainnya’.
“Seperti ketika ada pembakaran di Dago, itu yang menjaga jalanan, memblokir jalanan ya ibu-ibu dari Dago ini, yang akhirnya para driver ojek online jadi ikutan. Dari sana terlihat bahwa ternyata ibu-ibu pun mempunyai kekuatan untuk men-trigger satu gerakan,” kata Ayang.
Walau menurut Ayang pada awalnya pergerakan ibu-ibu masih belum terarah, tapi semuanya menjadi lebih terorganisasi dengan berbagai upaya edukasi hukum dan keterlibatan warga yang lebih banyak. Perlahan, mereka menyadari peran penting di ‘medan perang’ ini. “Oh, ternyata peran kita tuh nggak cuma di dapur doang ya. Oh, kita pun bisa bersuara ya, kita pun bisa berorasi, kita pun bisa menyampaikan suara-suara kita, yang kadang nggak didengar, yang mungkin di rumahnya (maaf-maaf) tidak dianggap oleh suaminya, oleh keluarganya,” lanjutnya.
Kesadaran politik ibu-ibu Dago Elos terus bertumbuh. Dalam pengalaman mereka, kehadiran perempuan di barisan depan aksi justru mampu meredam tindakan represif dan kekerasan lainnya. Inilah yang membakar semangat mereka dan membuat mereka mulai berani menyampaikan keluh kesah mereka, kerugian yang mereka rasakan dari konflik agraria ini. Baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Proses ini berlangsung organik dan menular, memantik keberanian perempuan di wilayah lain untuk ikut maju dan bersuara, salah satunya Sukahaji yang juga tengah mengalami konflik agraria.
Memantik keberanian perempuan di wilayah lain
Sebelum bisa bersolidaritas seperti ini, Dago Elos juga disemangati oleh ibu-ibu Kebun Jeruk, wilayah Kota Bandung yang juga mengalami konflik agraria. Tuti ingat betul saat itu melihat ibu-ibu Kebun Jeruk melakukan aksi sambil menggendong anak kecil. “Loh kok bisa ya? Kok berani ya? Saya masih merinding lihat dia,” katanya.
Setelah itu, ibu-ibu Dago Elos terus disemangati untuk mempertahankan dan melawan. Dibantu oleh solidaritas dari komunitas-komunitas lain, sedikit demi sedikit akhirnya Dago Elos percaya diri untuk bisa melawan. Sampai akhirnya bisa ikut menyemangati wilayah yang lain, seperti Sukahaji.
Menurut Tuti, tantangan saat mengorganisasi ibu-ibu di wilayah yang sedang menghadapi konflik seperti ini alah membangun fokus dan keberanian. Situasi itu kerap dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat. “Takut itu kan cepat menular ya. Jadi, ya sudah kalau nggak ditanamin dari diri kita sendiri, ya mau sama siapa lagi gitu kan,” katanya.
Menambahkan, menurut perspektif Ayang, ketakutan adalah hal yang wajar. Untuk itu, warga perlu diberi edukasi. Diedukasi tentang hukum, tentang haknya agar mereka tahu haknya untuk bersuara. “Kan banyak yang takut ditangkap, disantronin gitu. Di edukasi dulu hak anda apa? Kalau anda berhak untuk menyuarakan suara anda, nggak apa-apa kok. Kamu aman kok,” jelasnya.
“Jadi dengan hal-hal kecil aja. Tahu apa hak mereka itu aja gitu,”sambungnya.
Perempuan sebagai ikon perlawanan
Gerakan aktivisme nasional hari ini menempatkan ibu-ibu sebagai ikon. Pilihan itu, menurut Ayang, bukan tanpa risiko. Ada konsekuensi yang harus dihadapi, ada kerentanan yang menyertai. Namun, justru di situlah letak urgensinya.
Menurutnya sudah saatnya ‘Kartini-Kartini baru’ muncul karena jika tidak saat ini kapan lagi kita bisa membakar semangat perempuan. “Biar didengarlah. Dari sisi saya pribadi, (biar) nggak dianggap remeh gitu. Sudah banyak kan petinggi-petinggi bahkan presiden juga yang wanita gitu, ya. Jadi kenapa nggak mulai dari hal kecil seperti ini. Di titik-titik api kecil seperti kami ini, kita membakar semangat ibu-ibu untuk menyuarakan suara mereka,” lanjutnya.
Tak hanya bagi perempuan lain, aktivisme para ibu ini menjadi wajah yang juga dilihat anak-anaknya. Hamil dan memiliki anak yang masih balita tidak menyurutkan semangat Tuti. Meski sebenarnya tak ingin anaknya mengalami situasi sulit ini, tak bisa pula ia berdiam diri.

Ayang tak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika membicarakan dampak psikis konflik agraria ini pada anak-anak di Dago Elos. Saat terjadi bentrok, kampung mereka disatroni polisi. Kekerasan terjadi di depan mata anak-anak. Anak jadi gamang. Polisi yang mereka pelajari di sekolah berbeda dengan yang mereka temui di rumah.
Ayang sempat dipanggil ke sekolah anaknya. Lantaran anaknya marah kepada teman yang mengenakan seragam polisi di sekolah pada peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus. “Buka baju kamu. Polisi itu jahat. Kamu nggak boleh pakai baju itu nanti kamu ikutan jahat,” kata Ayang menirukan ucapan anaknya kepada temannya.
Kenyataan hidup anak-anak Dago Elos berbeda dengan anak-anak lain. Kondisi psikologis anak-anak tak mudah pulih.
Harapan dan Hadiah di Hari Ibu
Dengan banyaknya kepala, karakter, dan kepentingan yang berbeda, menjaga kekompakan bukan perkara mudah. Ayang dan Tuti sepakat, saling percaya menjadi fondasi yang harus terus dijaga. Pergesekan memang kerap terjadi, tetapi harus saling mengingatkan. “Jika satu mulai lelah atau terpancing emosi, yang lain berusaha meredam, nggak saling memanaskan keadaan, saling elingan,” kata Tuti.
Menjelang Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember, harapan Tuti justru terdengar sederhana, yaitu sabar, sehat dan semangat. “Kalau kita sehat lahir batin mau ada barang yang kita ingin atau enggak sudah bahagia gitu,” harap Tuti.
Baginya, tidak selalu soal kemewahan. Makan sederhana di depan dapur, dengan sambal seadanya, sudah terasa nikmat jika dijalani dalam kondisi sehat. Dari kesederhanaan itulah rasa syukur dirawat.
Lain halnya dengan Ayang. Tak tanggung-tanggung, ia ingin hidup lebih dengan layak, tinggal di luar negeri, berani bermimpi besar. Ia ingin membuktikan bahwa mereka yang hidup di kampung kota, yang kerap diremehkan, mampu bertumbuh dan membangun diri.
Salah satu wujudnya adalah keberanian berinvestasi pada pendidikan, bahkan di tengah konflik. Pada tahun-tahun genting itu, ia memilih menyisihkan penghasilan untuk melanjutkan pendidikan magister. Keputusan itu dijalani bersamaan dengan mengajar, mengurus keluarga, dan menghadapi proses hukum yang panjang. “Saya berpikir, sepuluh tahun ke depan, apa yang akan saya sesali kalau tidak saya lakukan sekarang,” tutur Ayang.
Pilihan itu berbuah. Ia menyelesaikan studi magisternya, mengajar di bidang keilmuannya, dan terus melanjutkan aktivismenya bersama ibu-ibu Dago Elos.
Aktivisme ibu-ibu Dago Elos mengingatkan kita, Hari Ibu bukan sekadar peringatan peran ibu di ranah domestik. Hari Ibu adalah merayakan keberanian perempuan menuntut haknya. Hidup ibu-ibu yang melawan! (Catur Ratna Wulandari) [*]