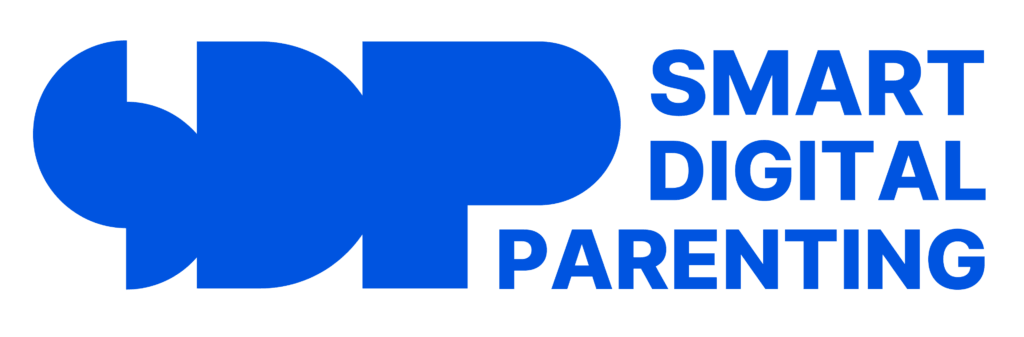Menjadi perempuan tidak mudah. Perempuan kerap dipaksa patuh pada kultur dan realitas sosial yang keliru juga penuh bias gender. Perempuan harus menikah, harus memiliki anak, dan harus melakukan kerja-kerja perawatan di rumah.
digitalMamaID — Perempuan sering dihadapkan pada realitas sosial yang penuh tekanan dan tuntutan. Ketika memilih bekerja, mereka dianggap abai terhadap keluarga. Ketika memilih menjadi pekerja rumah tangga, mereka dianggap menjadi beban suaminya.
Seorang perempuan tinggal di Jakarta, Lulu (32), bukan nama sebenarnya, mengaku bimbang ketika harus resign dari perusahaan tempatnya bekerja selama 5 tahun. Namun jika tidak berhenti, ia semakin sulit untuk membagi perannya sebagai perempuan pekerja, istri, juga ibu untuk anak-anak.
“Anakku sekarang sudah tiga dan suami sering keluar kota. Orangtua tinggal jauh di kampung. Kalau saya paksa bekerja saya keteteran, kerjaan jadi nggak maksimal dan kasihan juga anak-anak,” kata Lulu.
Mematahkan sebelah sayap demi kerja perawatan
Lulu pernah memakai jasa pembantu rumah tangga, namun hal itu justru memberinya persoalan lain. Ketidakcocokan cara kerja dan pertimbangan keamanan anak-anak, mendorongnya membuat keputusan besar. Ia relakan impiannya menjadi wanita karir. Ia tak lagi punya penghasilan sendiri. Semua kebutuhan ditopang oleh penghasilan suami.
Ia tinggalkan segala kesibukannya di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Hari-harinya kini dipenuhi dengan rentetan jadwal antar jemput anaknya sekolah, antar jemput anak les, menemani si bungsu bermain, membereskan rumah, mencuci baju, dan menyiapkan makanan.
Kondisi yang dialami Lulu ini jamak dialami perempuan Indonesia. Banyak perempuan yang terpaksa berhenti bekerja. Seperti mematahkan sebelah sayapnya, mereka menahan semua ambisinya. Semua itu karena sulit membagi peran dalam urusan kerja perawatan. Perempuan dianggap yang lebih bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rumah tangga. Tidak ada pembagian tugas yang setara.
Lain lagi kisah Rima (26), bukan nama sebenarnya. Ia berprofesi sebagai perawat yang kini tinggal di luar negeri. Statusnya yang masih lajang terus dibenturkan pada tuntutan masyarakat di desanya harus segera menikah. Tak kuasa melawan stigma, ia pergi meninggalkan kampung halamannya.
“Kapan nikah? Umur kamu sudah 26 tahun, kamu mau jadi perawan tua?” begitulah pertanyaan yang selalu dilontarkan padanya.
Melawan patriarki
Rima bukan menolak menikah. Ia hanya ingin menundanya sampai ia bertemu laki-laki yang berani mematahkan budaya patriarki. Ia hanya akan menikah dengan laki-laki yang bersedia membagi tanggung jawab secara setara, menjalankan perannya sebagai suami, ayah, dan anak laki-laki ibunya serta menghargai pendapatnya sebagai perempuan.
“Sekarang banyak wanita memilih tidak menikah karena selain tidak merasakan fungsi keberadaan suami, tingkat fatherless di Indonesia cukup tinggi,” ujarnya.
“Perempuan sekarang banyak yang berkarir, jika tugas suami dalam pernikahan hanya sekedar mencari nafkah, perempuan sendiri juga mampu. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menjadi tulang punggung keluarganya. Laki-lakinya? menganggur,” tambah Rima.
Rima tumbuh dalam keluarga patriarki. Ayahnya hanya tahu kerja di luar, sedangkan semua pekerjaan domestik sepenuhnya dilakukan oleh ibunya. Bahkan ia harus kehilangan adiknya karena ibunya keguguran dan ibunya masih harus kehilangan sebelah ginjalnya.
Di mata orang lain, ibunya adalah sosok perempuan pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Tetapi di mata Rima, ibunya adalah sosok perempuan paling rapuh yang bahkan tidak memiliki suara di rumah untuk sekedar bilang tidak.
Norma-norma di masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan berdiam di rumah, memberikan hak istimewa kepada laki-laki untuk tidak melakukan pekerjaan perawatan. Sedangkan, perempuan yang bekerja di luar rumah juga kerap mendapatkan stigma mengabaikan keluarga.
Habis waktu untuk kerja perawatan
Gender Officer Program Care Cis Timor, Lusia Carningsih Bunga atau yang akrab disapa Ningsih menyebutkan laki-laki sangat mendominasi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam sektor energi. Menurut Ningsih, transisi energi di NTT sangat jauh tertinggal dari NTB apalagi Jakarta. Salah satunya di kabupaten Sumba, masih banyak masyarakat yang memasak dengan mengandalkan kayu bakar dan minyak tanah, untuk mendapatkan air harus menimba di sumur yang jaraknya berkilo-kilo meter dari rumah.
“Jadi kalau perempuan di kota ketika mencuci bisa menggunakan mesin cuci karena sudah ada listrik, perempuan di kami harus mencari air dulu yang lokasinya jauh. Di kota kalau masak tinggal menggunakan listrik (magicom), perempuan di Sumba harus mencari kayu bakar dulu untuk memasak, meskipun sudah ada minyak tanah, sekarang sedang susah dicari,” ungkap Ningsih.
Ningsih mencontohkan, ada ibu rumah tangga yang rela harus bangun lebih pagi dan berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih. “Jam 3 pagi perempuan sudah ada yang bangun untuk menimba air, banyak aktivitas yang kecil-kecil itu dilakukan oleh perempuan, ini pekerjaan-pekerjaan tidak berbayar ini diperlekat lagi oleh norma yang ada di desa,” ujarnya.
Norma-norma yang melekat di masyarakat memposisikan perempuan hanya berperan di balik layar, yang tidak memiliki hak untuk tampil dan bersuara. Misalnya saja ketika perempuan harus menyiapkan adat leluhur, mereka harus menyiapkan persiapan-persiapan teknis untuk berlangsungnya ritual.
Laki-laki tahu, tapi tidak mau bertindak
Menurut Ketua Gema Alam NTB, Suhupawati, perempuan selalu dihadapkan dengan kerja-kerja perawatan yang bersifat rutinitas. Kerja-kerja tak berbayar ini yang kemudian mendesain perempuan menjadi tidak dihargai dan minim apresiasi. Padahal kerja-kerja perawatan sejatinya adalah tugas bersama.
“Perempuan memang lebih banyak menghabiskan waktu di kerja-kerja perawatan, sehingga kurang waktu untuk mendapatkan akses ke pengetahuan, pelatihan, pengembangan diri. Jika mereka ingin ikut pelatihan misalnya, akan banyak pertanyaan-pertanyaan di otaknya, nanti siapa cuci piring, masak, nyetrika, jemput anak, dan sebagainya,” kata Suhupawati
Sebuah penelitian dilakukan oleh The SMERU Institute menyebutkan, sudah banyak laki-laki yang sadar dengan kerja-kerja perawatan yang selama ini dilakukan oleh perempuan. Sebanyak 92 persen responden laki-laki setuju bahwa kerja perawatan merupakan tanggung jawab bersama. Namun dari 92 persen, hanya 12 persen responden laki-laki yang benar-benar mau melakukan kerja perawatan sedangkan 80 persen lainnya hanya omon-omon.
“Jadi 80 persennya itu omong doang. Kenapa bisa terjadi? kenapa ujung-ujungnya hanya perempuan. Di situlah norma berbicara,” kata peneliti The Smeru Institute, Dyah Utari.
Dyah melanjutkan, mereka yang mewajarkan kerja perawatan dilakukan juga oleh laki-laki adalah karena terbiasa. Sejak kecil, mereka sudah melihat kedua orangtuanya berbagi peran dałam kerja perawatan, sehingga apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya ia praktekkan dengan keluarga kecilnya saat ini.
“Sejak kecil mereka sudah terbiasa melihat ayahnya memegang sapu, mencuci piring, akhirnya mereka melihat dan mereka melakukan. Ketika mereka menikah pun, dia melakukan pekerjaan domestik sebagaimana yang ayahnya lakukan dulu. Jadi pekerjaan domestik itu tidak lagi menjadi aneh di matanya, karena ayahnya sudah mencontohkan,” kata Dyah. [*]