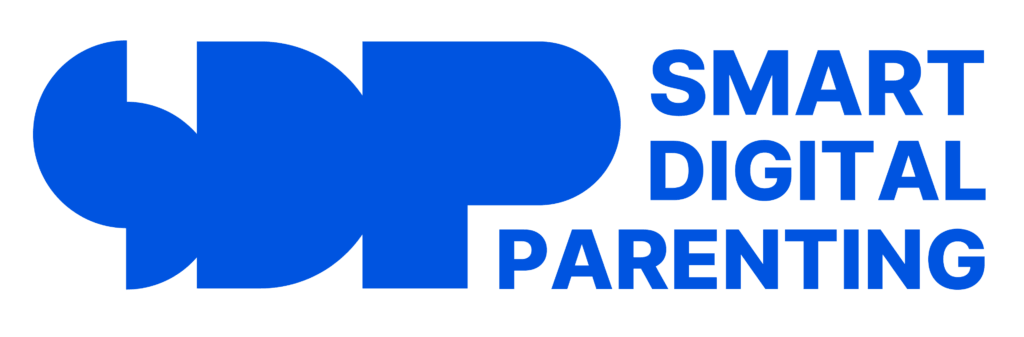digitalMamaID — Laras Faizati, seorang warga sipil, ditangkap pada awal September setelah unggahannya di media sosial dianggap menghasut pembakaran gedung Mabes Polri. Unggahan itu lahir dari kemarahan publik atas kematian seorang pengemudi ojek online. Hal itu membuat Laras dijerat pasal ITE dan kehilangan pekerjaannya. Kasus ini menyoroti bagaimana ekspresi di ruang digital masih mudah disalahartikan sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Pada Jumat, 29 Agustus 2025, setelah kematian pengemudi ojol, sebagaimana kemarahan seluruh rakyat Indonesia, Laras pun ikut menumpahkan rasa kekecewaan dan kemarahannya dalam unggahan media sosial Instagram, ‘When your office is right next to the National Police Headquarters, please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all protesters!!’.
Berselang beberapa hari, Laras pun ditangkap di kediamannya pada Senin, 1 September 2025 dengan jeratan Pasal 48 ayat 1 Jo, Pasal 45A Ayat (2) jo, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 161 Ayat (1) KUHP. Ia juga kemudian dipecat dari posisinya sebagai staf di ASEAN Inter‑Parliamentary Assembly (AIPA) setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Laras bukanlah satu-satunya orang yang ditangkap. Ada Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, Pegiat komunitas dari Kediri Saiful Amin, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, admin Blok Politik Pelajar Muzaffar Salim, pemilik akun Aliansi Mahasiswa Penggugat Khariq Anhar, dan masih banyak lagi pegiat dan warga sipil yang ditangkap dan dipidanakan dengan tuduhan penghasutan dan provokasi.
Melanggar kemerdekaan berpendapat
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, dalam dialognya di Kompas menyatakan, proses hukum Laras dan lainnya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Terutama soal kemerdekaan orang menyampaikan pendapat dan kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai media yang mereka miliki.
“Jadi kurang lebih melanggar pasal 28 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya dalam berbagai proses hukum tidak boleh dilanggar baik oleh aparat maupun pihak-pihak yang lain,” ungkap Feri.
Menurutnya, tuduhan bahwa pernyataan-pernyataan yang ada di media sosial merupakan bentuk penghasutan terasa dipaksakan dan mengada-ada. “Siapa yang menghasut, siapa yang dihasut, menurut saya terlalu sumir untuk kemudian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana,” sambungnya.
Ia menambahkan, jika ditelisik bukan hanya Laras dan lainnya, ada banyak orang di media sosial yang menyerukan untuk berani bersikap atau melawan. Bukan hanya ratusan ribu bahkan ada jutaan orang yang menyuarakan hal serupa saat itu.
“Media sosial adalah media informasi. Kalau saya menyebarkan informasi bahwa DPR mengatakan rakyatnya tolol, lalu kemudian hidup dengan gaya hedonistik, joget sana-sini, lalu saya sebarkan. Dan saya bilang bahwa ini tidak elok, tidak baik. Yang menghasut itu pernyataan saya atau tindakan DPR? Kalau publik marah karena tindakan DPR, maka DPR harus dinyatakan sebagai orang yang melakukan penghasutan karena orang marah begitu ya,” katanya.
Dugaan pelanggaran HAM
Lebih lanjut lagi, Feri menilai penangkapan ini sebagai pelanggaran HAM juga pelanggaran konstitusional. “Kausalitas itu kan juga harus logis ya. Misalnya apakah mungkin pelaku membakar sesuatu karena apa yang dia tonton di medsosnya Mbak Laras. Bagaimana bisa membuktikan bahwa pelaku pembakaran melakukan tindakan karena menonton medsos Mbak Laras, wong pelakunya saja belum tertangkap?,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dasar logika yang digunakan aparat penegak hukum dalam membangun tuduhan tersebut. Aparat seolah sedang mencari-cari kesalahan dan sosok yang bisa dijadikan kambing hitam, padahal tidak ada logika hukum yang benar dalam proses itu.
Prinsipnya dalam proses penegakan hukum, penghormatan terhadap konstitusi harus dijunjung tinggi. Proses hukum, menurutnya, tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hanya demi menemukan pihak yang dianggap bersalah. Ia juga mengingatkan bahwa jika logika penalaran hukum tidak runut sejak awal, maka unsur-unsur yang hendak dibuktikan nantinya akan menjadi berantakan.
“Paling penting itu polisi dan aparat penegak hukum tidak asal. Dan tidak boleh polisi mengatakan ‘tempuh saja jalur hukum praperadilan’. Loh kan harusnya orang juga diberikan haknya. Kenapa dia dituding? Apa alasannya? Apa buktinya? Disampaikan secara terbuka kepada publik,” tuturnya.
“Kan polisi punya hak ya untuk menyampaikan apa yang dia rasa benar. Tetapi publik juga punya hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditudingkan,” lanjutnya.
Suara perempuan
Tertanggal 21 Oktober 2025 lalu, Laras menulis surat melalui LBH APIK menyampaikan bahwa dirinya telah dilimpahkan menjadi tahanan jaksa dan akan berada di Rutan Bambu Apus, bukan lagi di Bareskrim Polri. Ia meminta doa dan dukungan publik agar dirinya dan teman-teman yang kini menjadi tersangka mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Laras menyatakan bahwa mereka yang dijadikan tersangka dikriminalisasi. Ia menegaskan bahwa suara mereka seharusnya didengar dan menjadi kekuatan untuk kemajuan bangsa, bukan dibungkam. Di bagian penutup, Laras mengajak teman-teman dan pendukungnya untuk tetap sehat, kuat, dan berharap bisa bertemu di luar jeruji.
Kasus Laras Faizati memperlihatkan bagaimana ruang ekspresi di ranah digital masih rentan ditafsirkan sebagai ancaman, bukan sebagai wujud kebebasan warga negara. Terlebih bagi perempuan, suara kritis kita sering kali ditafsirkan berbeda, dianggap provokatif, emosional atau menyalahi batas moralitas.
Ketika kebebasan berbicara dan berpendapat, perempuan kerap disalahartikan, maka risiko kriminalisasi menjadi semakin besar terutama di tengah sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kesetaraan. Dalam konteks itu, pemberlakuan KUHP Nasional pada 5 Januari 2026 nanti agaknya banyak menimbulkan kekhawatiran baru.
Sejumlah pasalnya berpotensi mempersempit ruang gerak dan kebebasan perempuan sebagai kelompok rentan, terutama melalui tafsir moralitas dan kesusilaan yang bias gender. Alih-alih melindungi, hukum bisa menjadi alat baru untuk menegakkan kontrol terhadap tubuh dan suara perempuan. [*]