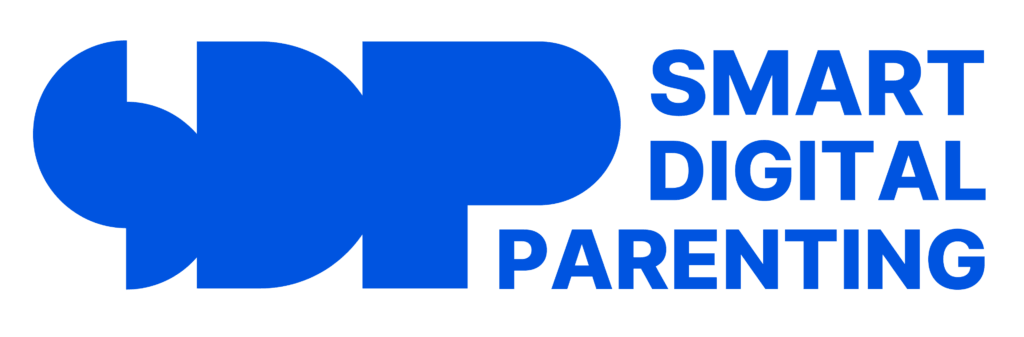Peringatan: Artikel ini membahas bunuh diri dan kekerasan keluarga. Jika Mama sedang mengalami depresi atau memiliki kecenderungan bunuh diri, segera hubungi layanan kesehatan jiwa terdekat atau tenaga profesional.
Bandung, kota yang sering dipuji dengan segala romantisme kreativitas dan kultur budaya para muda-mudinya yang menebarkan keramahan dan keceriaan, dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi saksi bisu tragedi yang mengguncang nurani publik. Seorang perempuan muda berusia 19 tahun ditemukan tak bernyawa di area parkir King’s Shopping Center, diduga jatuh dari lantai sebelas. Beberapa hari sebelumnya, berita lain dari Kabupaten Bandung juga hadir penuh luka: seorang ibu berusia 34 tahun memilih mengakhiri hidupnya, bersama dua anaknya, karena jeratan kesulitan ekonomi yang tampaknya tidak menemukan jalan keluar.
Kedua peristiwa ini, meskipun berbeda tempat dan alasan kejadian, terikat oleh benang merah yang sama: kesehatan mental yang rapuh, terbebani oleh impitan sosial-ekonomi yang kian menjerat, tanpa adanya sistem penopang yang mampu menahan langkah terakhir seseorang sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kita bisa saja menganggapnya sebagai kasus individual, sekadar berita duka yang datang dan pergi, namun bila dilihat lebih dalam, keduanya mencerminkan kegagalan sistemik yang jauh lebih luas: kegagalan negara dalam menjamin kehidupan yang layak sekaligus mengabaikan kebutuhan mendesak akan dukungan kesehatan mental.
Dalam psikologi modern, bunuh diri tidak lagi dipandang semata sebagai “pilihan pribadi” yang berdiri seolah tanpa pilihan. Teori diathesis-stress model, misalnya, menjelaskan bagaimana seseorang membawa kerentanan tertentu, bisa berupa trauma masa lalu, gangguan mood, atau predisposisi biologis, yang kemudian bertemu dengan tekanan eksternal akut seperti kehilangan pekerjaan, utang menumpuk, atau retaknya relasi keluarga. Pertemuan dua faktor itu bisa mendorong individu pada titik di mana dunia tampak buntu. Dalam konteks lain, Martin Seligman memperkenalkan konsep learned helplessness: kondisi ketika individu yang terus-menerus gagal menemukan solusi akhirnya berhenti mencoba, merasa tidak ada jalan keluar, dan meyakini hidupnya tidak lagi bisa diperbaiki.
Kedua kasus dari Bandung tadi, memperlihatkan bagaimana teori-teori itu berwujud nyata. A, remaja yang ditemukan di Kings, berada dalam fase usia yang oleh banyak psikolog disebut rentan: masa transisi menuju dewasa, di mana identitas, relasi sosial, dan tekanan ekonomi saling berebut ruang. Sedangkan kasus EN jauh lebih kompleks, karena melibatkan anak-anak. Surat wasiat yang ditinggalkan memperlihatkan bukan hanya keputusasaan personal, tetapi juga jeratan ekonomi struktural yang memaksa seorang ibu melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi keluarganya. Pada titik ini, bunuh diri tidak lagi bisa dipandang sebagai keputusan individu, melainkan sebagai sebuah gejala sosial yang lahir dari kombinasi kemiskinan, keterasingan, dan ketiadaan jaminan hidup yang layak.
Kita hidup di tengah dunia yang kerap mengagungkan optimisme pembangunan secara struktural, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dijadikan indikator tunggal kesejahteraan. Namun, kasus-kasus seperti ini memperlihatkan jarak menganga antara klaim makroekonomi dengan kenyataan mikro di dapur tiap-tiap individu warga. Angka-angka yang indah dalam laporan negara tidak mampu menutupi kenyataan pahit bahwa ada keluarga yang tidak lagi mampu membeli makanan layak, ada ibu yang merasa bersalah karena tidak dapat memberi masa depan pada anaknya, dan ada remaja yang merasa dunia tidak menyediakan ruang aman untuknya. Sosiolog dengan tepat menyebut fenomena bunuh diri karena faktor ekonomi ini sebagai bentuk fenomena sosial; ia bukan penyimpangan individual, melainkan refleksi dari kondisi masyarakat yang rapuh.
Di titik inilah pentingnya kehadiran negara menjadi tak terbantahkan. Negara tidak bisa sekadar hadir sebagai aparat yang datang mencatat laporan kematian, melainkan harus hadir sebelumnya: di ruang-ruang pencegahan, di meja dapur keluarga yang kesulitan membeli beras, di ruang kelas anak yang terancam putus sekolah, dan di hati warga yang terjerat kecemasan. Kehadiran negara berarti memastikan jaring pengaman sosial bekerja secara nyata, bukan sebatas jargon. Ia berarti memberi akses pada bantuan tunai yang cepat tanpa birokrasi berbelit, memastikan puskesmas memiliki layanan konseling dasar yang bisa dijangkau warga miskin, dan membangun mekanisme respons darurat ketika ada sinyal bahaya dari individu yang sedang mengalami krisis mental.
Namun, kehadiran negara saja tidak cukup bila tidak dibarengi dengan perubahan budaya publik dalam memandang kesehatan mental secara utuh, dan berkelanjutan. Stigma masih begitu kuat, membuat banyak orang menutup rapat penderitaan psikisnya. Kampanye darurat kesehatan mental harus hadir sebagai upaya kolektif untuk menormalisasi percakapan tentang depresi, kecemasan, dan trauma, sekaligus mengajarkan langkah-langkah sederhana untuk mendampingi orang terdekat yang menunjukkan tanda bahaya. Kampanye itu tidak bisa berhenti pada poster atau slogan di jalan raya; ia harus diwujudkan dalam layanan nyata seperti hotline krisis 24 jam, pelatihan psychological first aid bagi aparat desa, dan program pendampingan berbasis komunitas yang mampu menjangkau mereka yang paling terisolasi.
Sebagian orang mungkin akan berkata bahwa negara sudah terlalu banyak beban, dan bahwa masalah pribadi harus ditanggung individu masing-masing. Namun pandangan itu lupa pada satu hal mendasar: kesehatan mental bukan hanya urusan pribadi, melainkan urusan publik. Depresi seorang ayah yang kehilangan pekerjaan bisa berujung pada kekerasan domestik. Kecemasan seorang remaja yang merasa gagal bisa berujung pada percobaan bunuh diri. Keputusasaan seorang ibu miskin bisa menyeret serta nyawa anak-anaknya. Efek domino dari kesehatan mental yang rapuh tidak berhenti di ruang individu, melainkan merembet ke keluarga, komunitas, bahkan bangsa secara luas. Itulah sebabnya negara perlu memperlakukannya sebagai darurat.
Jika kita membaca dua kasus ini dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa yang sebenarnya mati bukan hanya A atau EN dan anak-anaknya, tetapi juga rasa keadilan sosial kita. Mereka adalah cermin betapa janji “hidup layak bagi setiap warga negara” masih terasa utopis. Dan selama tragedi seperti ini terus berulang, setiap slogan pembangunan yang dideklarasikan di panggung politik akan terdengar hampa.
Namun, refleksi ini tidak boleh berhenti pada rasa iba semata. Tragedi harus menjadi titik balik. Bandung—dan Indonesia pada umumnya—memerlukan sebuah strategi nasional yang memandang kesehatan mental dan kemiskinan sebagai dua sisi koin yang saling terkait. Tidak ada kesehatan mental tanpa keadilan sosial, dan tidak ada keadilan sosial tanpa perhatian serius pada kesehatan mental. Kedua dimensi itu harus ditangani bersamaan, bukan dipisahkan dalam kementerian atau birokrasi yang bekerja sendiri-sendiri.
Esai ini ditutup dengan satu keyakinan sederhana: setiap nyawa yang hilang karena keputusasaan adalah tanda bahwa negara terlambat hadir. Tugas kita bersama adalah memastikan keterlambatan itu tidak lagi menjadi pola. Jalan yang terasa buntu bagi mereka yang pergi harus kita buka kembali menjadi jalur harapan, lewat kebijakan yang berpihak, layanan yang nyata, dan solidaritas yang tidak hanya berhenti pada kata-kata. Jika tidak, maka kita akan terus membaca berita serupa, berkali-kali, hingga rasa kehilangan ini menjadi rutinitas, dan itu adalah bentuk kegagalan paling besar sebagai sebuah bangsa.
Foggy FF
Seorang penulis novel, cerpenis dan penulis esai di beberapa platform digital. Ia aktif berkampanye tentang isu sosial, perempuan dan kesehatan mental. Penulis dapat dihubungi melalui Instagram @halamanhalimun dan email halamanhalimun@gmail.com