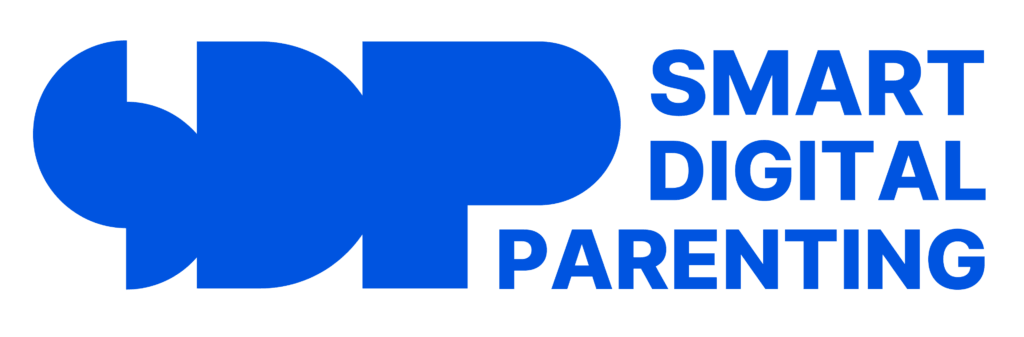digitalMamaID — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, resmi akan berlaku efektif pada 2026. Memuat sejumlah ketentuan baru, diantaranya living law, judicial pardon dan pidana korporasi. KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, setelah 70 tahun mengadopsi KUHP warisan kolonial Belanda.
Akan tetapi, perubahan besar ini di satu sisi juga menimbukan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil, aktivis, pegiat, juga akademisi. Beberapa pasal yang ada di dalamnya dinilai multitafsir, yang berpotensi terjadi kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok rentan terutama perempuan. Salah satu yang mendapat perhatian, adalah pasal perzinahan (Pasal 411) dan kohabitasi atau hidup bersama di luar pernikahan (Pasal 412).
Walau pemerintah berdalih ketentuan ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan nilai keluarga. Tetapi bagi banyak pihak, ketentuan tersebut justru bertentangan dengan prinsip hak atas privasi serta non-diskriminasi. Pasal-pasal ini dinilai membuka ruang intervensi negara dalam ranah privat warga negara, sekaligus memberi celah untuk menarget perempuan, kelompok minoritas seksual atau pasangan rentan.
Dalam konteks ini, perempuan menanggung beban paling berat. Stigma sosial kerap diarahkan kepada perempuan. Dalam kasus hubungan di luar nikah yang diketahui publik, perempuan bisa dipermalukan, diusir dari tempat tinggalnya, kehilangan pekerjaan, bahkan dilaporkan ke pihak berwajib.
Situasi ini tercermin dalam tragedi di Cikupa, Tangerang pada bulan November 2017 dimana warga menggerebek, menelanjangi, mengarak, dan melakukan kekerasan terhadap pasangan yang diduga mesum karena tinggal bersama. Aparat pun kemudian bukannya menindak tegas para pelaku kekerasan tersebut, malah ikut andil memfasilitasi ancaman dan pelanggaran lanjutan dengan memediasi bahkan melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap korban.
Perburuk nasib korban kekerasan seksual
Kondisi ini juga berpotensi memperburuk nasib perempuan korban kekerasan seksual. Alih-alih mendapat perlindungan, korban justru bisa berbalik menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap melanggar pasal-pasal tersebut, terutama ketika pelaku berdalih bahwa hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Padahal banyak kasus kekerasan seksual terjadi akibat relasi kuasa, tipu daya, atau gaslighting yang membuat korban tidak berdaya.
Direktur LBH Bandung Heri Pramono menilai pasal-pasal ini menyinggung sektor privat dan berpotensi meminggirkan korban. Negara, menurutnya kerap melihat objektivitas kejadian hanya dari kacamata formal, bukan dari pengalaman subjektif korban.
“Kerentanannya memang ada di perempuan. Bahkan kerentanan yang berlapis ketika mereka dikucilkan terus menjadi stigma bagi masyarakat,” paparnya pada digitalMamaID Selasa, 11 November 2025.
Senada, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia Khotimun Sutanti, menilai pasal ini akan semakin membungkam korban kekerasan seksual. Menurutnya tekanan sosial, keluarga dan institusi yang selama ini sudah berat akan semakin besar.
“Untuk berani mengadukan atau melaporkan bahwa dia adalah korban kekerasan seksual itu butuh banyak kesiapan, kesiapan psikologis terutama ketika dia harus berhadapan dengan peradilan, berhadapan dengan proses hukum, berhadapan dengan masyarakat, dengan teman-teman sendiri, dengan keluarga itu tidak mudah,” ungkap Khotimun pada digitalMamaID Kamis 20 November 2025.
“Sekarang bertambah satu lagi, berhadapan dengan pasal ini,” sambungnya.
Berdasarkan pengalamannya mendampingi, Khotimun menambahkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual melibatkan relasi kuasa, rangkaian kebohongan, manipulasi dan sebagainya. Pelaku tidak mengaku begitu saja, melainkan mengklaim bahwa perbuatannya suka sama suka. Sehingga korban tidak bisa atau sulit membuktikan bahwa dirinya adalah korban.
Heri pun menegaskan situasi ini diperburuk dengan banyaknya aparat penegak hukum yang belum berperspektif korban dan bias gender, dalam artian beberapa kasus yang melibatkan perempuan, penyidiknya adalah laki-laki. Hal ini membuatnya merepresentasikan bahwa negara belum siap melihat dari kacamata gender.
“Lebih menampilkan bagaimana dia berkaitan, tidak memperhatikan relasi kuasa, tidak memperhatikan dari dampak kekerasan gender tersebut. Sehingga itu yang membuat kami jadi terhambat di dalam beberapa pendampingan-pendampingan terkait dengan kasus-kasus perempuan atau gender,” ungkap Heri.
Ancaman persekusi yang lebih parah
Persoalan menjadi lebih sulit bagi korban untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya karena rentan terjadi persekusi. “Razia-razia yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, bisa dilakukan lebih sewenang-wenang menggunakan pasal ini,” jelas Khotimun.
Walaupun dalam perundang-undangan dijelaskan razia bukan wewenang mereka, praktik tersebut tetap saja berlangsung meski tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kehadiran pasal ini dikhawatirkan memberi legitimasi baru bagi tindakan razia dan persekusi yang berpotensi adanya kekerasan.
Dampak juga tidak hanya dirasakan korban kekerasan seksual, tetapi perempuan yang menikah siri atau perempuan adat yang terhambat mengakses akta perkawinan. Karena tidak diakui negara, mereka pun rentan dipidana.
Menurut LBH APIK, pidana bagi pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi) jelas tidak mempertimbangkan situasi sosial di masyarakat. Karena realitanya terdapat masyarakat yang masih terhambat dalam mengakses akta perkawinan, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara.
“Seperti praktek “baku piara” karena kesulitas membayar belis (mas kawin atau harta adat). Mereka juga rentan dipidana karena ketentuan ini,” katanya.
Delik aduan absolut, benarkah ini fair?
Kedua pasal tersebut menggunakan delik aduan absolut artinya hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pemerintah menilai mekanisme ini sebagai jalan tengah dan sudah cukup membatasi ruang kriminalisasi.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Dhahana Putra dikutip dari Antara mengatakan, wujud perlindungan dari ruang privat masyarakat adalah dengan diaturnya dua jenis delik itu sebagai delik aduan. Artinya, tidak pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari mereka yang berhak mengadu karena dirugikan secara langsung.
Menurut Dhahana, secara a contrario (menurut pengingkaran), pengaturan tersebut juga berarti menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri.
Namun, sejumlah ahli menilai bahwa mekanisme delik aduan absolut tetap menyimpan risiko, terutama dalam konteks masyarakat yang patriarkal. Khotimun menilai, ini bisa menjadi dalih bagi keluarga untuk bertindak atas “nama baik” keluarga atau moralitas. “Korban kekerasan seksual ini ditekan untuk menikah, entah menikah dengan pelaku atau menikah dengan yang lainnya gitu. Nah itu menambah kerentanan,” katanya.
Senada, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (UNPAR), Nefa Claudia Meliala pun menyampaikan beberapa catatannya terkait delik aduan absolut. Menurutnya, menempatkan orang tua menjadi pihak yang mengadukan. Menurutnya, satu hal yang harus dicermati adalah adanya potensi peningkatan perkawinan anak usia dini yang dianggap sebagai “jalan keluar” dari jerat pidana.
Orang tua akan berpikir daripada di proses secara hukum, lebih baik dinikahkan di usia dini. Padahal perkawinan itu bukan jawaban dari persoalan kompleks yang mungkin menjerat anak-anak yang berperilaku menyimpang. Pemaksaan pernikahan terhadap anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan data United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dari data tersebut, Indonesia menduduki peringkat empat dengan kasus perkawinan usia dini terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh, dan Cina.
Sementara itu Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mencatat pada rentang 2019-2023, sebanyak 95 persen permohonan dispensasi kawin dikabulkan pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Adapun sepertiga alasan yang diajukan pada permohonan dispensasi itu adalah kehamilan pada anak.
Nefa juga menyoroti risiko lain, ketika menempatkan anak juga sebagai pelapor sama saja menempatkan anak dalam posisi rentan karena bisa saja anak dimanfaatkan atau dipengaruhi salah satu orang tua yang berkonflik.
“Padahal kalau kita berhitung, itu impact-nya juga buruk sebetulnya untuk anaknya. Jadi ada potensi buruk terhadap anak secara psikis ya. Jadi itu hal-hal yang juga harus diperhatikan, mempertimbangkan prinsip best interest of the child,” terangnya.
Celah hukum dari pasal perzinahan
Pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Nefa mengurai beberapa catatan mengenai pasal ini. Menurutnya, yang menjadi problematik dalam pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional ini pertama adalah karena adanya perluasan pasal.
“Kalau kita compare dengan KUHP lama, KUHP lama sebetulnya daya jangkaunya hanya penjelasan pasal 411 ayat (1) huruf A sampai D KUHP baru. Sekarang ditambahkan kategori baru huruf E, bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dan melakukan persetubuhan, itu pun masuk dalam kategori perzinaan,” jelas Nefa pada digitalMamaID Selasa, 18 November 2025.
Jika di telaah lebih lanjut, dalam penjelasan pasal terdapat kata kunci ‘terikat dalam perkawinan’ atau ‘tidak terikat dalam perkawinan’. Menurut Nefa, kalimat ‘ikatan perkawinan’ ini tidak jelas maknanya.
“Dalam KUHP Nasional tidak ada definisi yang dimaksud apa itu ‘ikatan perkawinan’. Ini penting karena nanti dalam konteks penegakan hukum unsur itu harus dibuktikan satu persatu dan untuk membuktikan kita harus tahu definisinya,” jelasnya.
Menurut Nefa, dalam ilmu hukum ada yang disebut dengan metode penafsiran hukum. Di dalamnya ada macam-macam penafsiran, salah satunya penafsiran sistematis. Jika penjelasan tidak cukup jelas dalam undang-undang yang sedang dipelajari, maka harus mengacu pada undang-undang lain yang membantu agar lebih terang dan jelas.
Dalam konteks ini, menurutnya perlu untuk melihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, soal syarat sah perkawinan yang berkaitan dengan unsur “ikatan perkawinan” yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional. Menurutnya ada dua pandangan, pandangan pertama mengatakan bahwa perkawinan sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing. Tapi, pandangan kedua melihatnya berbeda, bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah perkawinan.
Jadi perkawinan yang tidak tercatat disebut perkawinan tidak sah. Sekalipun sah berdasarkan agama atau kepercayaan, sah berdasarkan adat istiadat tapi, tidak tercatat dikategorikan sebagai perkawinan tidak sah.
Bisa menjerat pasangan yang tak tercatat secara administratif
Sampai hari ini menurutnya hal ini masih jadi persoalan. “Problem-nya adalah bahwa tidak dicatatkannya satu perkawinan yang sudah dilangsungkan, itu kan alasannya bisa macam-macam. Mungkin penyebabnya salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, atau persoalan keterbatasan ekonomi karena perlu biaya untuk mencatatkan,” papar Nefa.
“Itu persoalan-persoalan di luar persoalan hukum yang kemudian juga berdampak pada persoalan keabsahan satu perkawinan. Kita harus melihat itu secara jernih. Jadi, bisa beragam alasannya kenapa orang tidak mencatatkan perkawinan,” sambungnya.
Konsekuensinya, ketika ada laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan secara agama atau secara adat, mereka bisa dianggap sebagai laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
“Jika logikanya seperti itu, pasangan ini potensial dijerat dengan delik perzinaan. Pertanyaannya adalah apakah tidak mencatatkan perkawinan adalah satu kejahatan sehingga perlu dilaporkan ke polisi? Ini kan pertanyaan yang penting untuk menjadi refleksi bersama karena konstruksi pasalnya kan demikian,” katanya.
Termasuk jika membaca ketentuan pasal 404 KUHP Nasional, itu disebutkan, “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II”. Artinya, orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya potensial juga dijerat Pasal 404 KUHP Nasional.
Ketidajelasan unsur persetubuhan
Selain persoalan “ikatan perkawinan”, Nefa juga menyoroti unsur persetubuhan dalam pasal perzinaan. Menurutnya, tidak ada definisi jelas mengenai ‘persetubuhan’ dalam KUHP Nasional. Sehingga lagi-lagi harus mengacu ke sumber hukum lain misalnya putusan Hoge Raad, pendapat pakar, ahli atau doktrin.
Persetubuhan itu mensyaratkan harus ada penetrasi alat kelamin pria kepada alat kelamin wanita. Dalam konteks hukum, jika dikatakan ada persetubuhan yang terjadi, maka harus dibuktikan bahwa penetrasi itu benar-benar terjadi. Jika tidak bisa dibuktikan, tidak bisa disebut sebagai persetubuhan.
“Misalnya ada laki-laki dan perempuan, mereka ada dalam satu ruangan tertutup. Kita nggak bisa pakai asumsi bahwa karena mereka lawan jenis kemudian mereka bersetubuh karena mereka ada dalam satu ruang tertutup. Pembuktiannya harus dengan standar bahwa memang ada penetrasi tadi. Itu mengacu pada sumber hukum seperti doktrin atau putusan pengadilan tadi saya sebutkan, putusan Hoge Raad misalnya,” jelasnya.
Nefa juga mengingatkan bahwa persetubuhan berbeda dengan kekerasan seksual. Persetubuhan mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, tanpa paksaan, tanpa relasi kuasa atau tipu daya. Bila terdapat unsur tipu daya, paksaan, relasi kuasa, itu masuk dalam kategori kekerasan seksual.
“Ini catatan yang penting juga berkenaan dengan pembuktian persetubuhan, bahwa jangan sampai, ada seorang perempuan yang sebetulnya adalah korban kekerasan seksual. Dia menjadi korban untuk kedua kalinya karena perempuan ini dituduh melakukan persetubuhan,” katanya.
Banyak kasus-kasus secondary victimization yang terjadi, korban menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Padahal seharusnya dilindungi secara hukum tapi, justru dituduh sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu perlu kejelian dan kehati-hatian dalam melihat sebuah kasus karena terkadang problematik dalam praktiknya.
Celah Pasal 412 Kohabitasi
Pasal Kohabitasi 412 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Nefa menilai pasal kohabitasi ini tidak jelas hendak melindungi apa sebenarnya. Jika untuk melindungi lembaga perkawinan, tentu kaitannya juga dengan hubungan seksual karena hubungan seksual itu dilakukan dalam perkawinan dan hendak di proteksi undang-undang, agar tidak sembarangan dilakukan oleh orang-orang yang tidak semestinya melakukan itu.
“Padahal hubungan seksual di luar perkawinan itu juga sudah diatur di dalam pasal perzinaan. Jadi ada semacam overlap nih, ada tumpang tindih,” jelasnya.
Dikarenakan overlap atau tumpang tindih, ini akan menyulitkan proses pembuktian. Kemungkinan menurutnya, akan ada perdebatan pasal mana yang akan digunakan, perzinaan atau kohabitasi karena sanksinya masing-masing berbeda. Hal ini bisa menimbulkan potensi-potensi masalah juga jika terjadi tawar-menawar pasal yang akan disangkakan.
Di pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional juga disebutkan, “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”. Penjelasan unsur ini lagi-lagi tidak ada di dalam KUHP Nasional. Nefa kembali menggunakan tafsir sistematis mengacu pada Undang-Undang Perkawinan.
Menurutnya Pasal 32 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan ayat (1), “Suami istri harus punya tempat kediaman yang tetap”, ayat (2) “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama”.
Kemudian Pasal 33 disebutkan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, lalu ayat (2), “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.
“Bagaimana membaca Pasal 32 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan itu menjadi penting karena itu menjadi parameter apakah memang mereka hidup bersama layaknya suami istri. Jadi harus dibuktikan bahwa ketentuan Pasal 32 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan tadi terpenuhi supaya paling tidak standarnya jelas. Untuk menghindari juga tumpang tindih dengan pasal perzinaan,” terangnya.
Sadar akan hak
Catatan hukum yang dipaparkan Nefa menunjukkan betapa luasnya ruang tafsir yang dapat muncul dalam implementasi Pasal 411 dan 412 jika tidak ada parameter yang jelas. Temuan ini sejalan dengan kekhawatiran LBH APIK dan LBH Bandung, yang menilai perempuan akan menjadi kelompok paling rentan, baik sebagai objek aduan maupun objek kriminalisasi, terutama dalam relasi kuasa yang timpang. Semua catatan tersebut menegaskan bahwa persoalan Pasal 411 dan 412 bukan semata soal moral atau keluarga, melainkan persoalan hukum yang membawa risiko besar terhadap hak asasi dan keamanan perempuan.
LBH Bandung sendiri, sejak 2023, telah berjejaring dengan berbagai koalisi untuk menyisir pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil dan menyiapkannya untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Khotimun menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sekaligus mendorong implementasi UU TPKS yang hingga kini belum sepenuhnya digunakan. Di lapangan, aparat lebih memilih menggunakan KUHP, padahal pasal-pasal kesusilaan di KUHP tidak tepat untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ia menilai, pelanggaran terhadap tubuh dan martabat seseorang seharusnya dipisahkan dalam subbab yang berbeda agar penanganannya lebih jelas.
Melihat kondisi ini, Heri mengajak masyarakat sipil untuk lebih sadar akan hak-haknya. “Kita kan nggak bisa ya menunggu KUHP berubah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sadar hak, sadar hak ketika ditetapkan sebagai tersangka, sadar hak ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, sadar hak ketika diperiksa sebagai warga negara,” pungkasnya.[*]